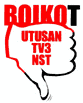Kiriman daripada Seberang:
'Tales of the two presidents'
Oleh Daniel Dhakidae
M@RHAEN menyiarkan bahan yang dikirimkan oleh pengunjung laman M@RHAEN daripada negara seberang Selat Melaka untuk bacaan dan renungan kita bersama. M@RHAEN tidak melakukan sebarang suntingan, sebaliknya mengekalkan penggunaan bahasa Indonesia seperti teks asal yang diterima.
BIOGRAFI yang ditulis oleh orang lain, apalagi dalam kategori "as told to" selalu membagi dua pendapat antara yang memuja dan mencaci-makinya. Tentang biografi semacam itu sastrawati Inggris, profesor sastra dari University College, London, AS Byatt, mengatakan sebagai:... bentuk rusak dan upaya mengejar pengetahuan murahan. Cerita tuturan mereka yang tidak mampu menangkap penemuan sejati, cerita sederhana bagi orang yang tidak mampu menyelam lebih dalam. Bentuk rumpi dan kekosongan jiwa yang sakit. (On Histories and Stories, Selected Essays, dalam The New York Times, 18 Maret 2001).
Penilaian sekeras ini kontra-produktif karena kalau semata-mata itu yang dipakai, hampir tidak terbuka kemungkinan mengenal seorang lain melalui naskah-naskah warisan.
"Tales of the two presidents"
Ini juga berlaku dalam hal dua orang yang pernah menjadi presiden Indonesia. Presiden Soekarno dan Soeharto, sama sekali tidak ada waktu menulis otobiografinya sendiri, karena itu suasana batinnya tidak pernah diketahui umum secara "asli". Soekarno dengan seluruh kemampuan intelektualnya untuk merenung, mencernakan, dan menulis tidak pernah meluangkan waktu menulis tentang dirinya sendiri selain beberapa keping cerita anekdotal yang tercecer sana-sini. Soeharto tidak pernah terbukti menulis sesuatu yang berarti untuk publik, selain pidato-pidato kepresidenan dengan intervensi begitu banyak tangan dan otak.
Namun, kalau biografi "as told to" menjadi satu-satunya sumber yang bisa dipakai, maka berikut ini adalah "ucapan asli" dengan mana kedua presiden itu mengungkapkan dirinya--Soekarno kira-kira beberapa waktu sebelum atau di sekitar tahun 1965 kepada penulis Amerika, Cindy Adams, dalam buku Sukarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, pada saat Soekarno berumur 65 tahun; Soeharto kira-kira beberapa waktu sebelum atau di sekitar tahun 1989 kepada dua penulis Indonesia, Dwipayana dan Ramadhan, dalam buku Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Otobiografi Seperti Dipaparkan Kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H., pada saat Soeharto berumur kira-kira hampir sama, 67 tahun.
Membandingkan apa yang dikatakan kedua orang ini tentang dirinya mungkin bisa memberikan wawasan tentang kepribadiannya masing-masing dan apa yang dibuatnya. Tentang dirinya Soekarno mengatakan:
"Aku adalah putra seorang ibu Bali dari kasta Brahmana. Ibuku, Idaju, berasal dari kasta tinggi. Raja terakhir Singaraja adalah paman ibuku. Bapakku dari Jawa. Nama lengkapnya adalah Raden Sukemi Sosrodihardjo. Raden adalah gelar bangsawan yang berarti "Tuan". Bapak adalah keturunan Sultan Kediri... Apakah itu kebetulan atau suatu pertanda bahwa aku dilahirkan dalam kelas yang memerintah, akan tetapi apa pun kelahiranku atau suratan takdir, pengabdian bagi kemerdekaan rakyatku bukan suatu keputusan tiba-tiba. Akulah ahli-warisnya.
Suatu yang sangat berbeda berlangsung dengan Soeharto, yang tentang dirinya berkata:
Ayah saya, Kertosudiro, adalah ulu-ulu, petugas desa pengatur air, yang bertani di atas tanah lungguh, tanah jabatan selama beliau memikul tugasnya itu... Saya adalah keturunan Bapak Kertosudiro alias Kertorejo ...yang secara pribadi tidak memiliki sawah sejengkal pun.
Bila diperhatikan ada beberapa perbedaan besar yang menarik perhatian antara keduanya. Pertama, keturunan ningrat langsung saja diangkat Soekarno, baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak. Dari pihak ibu garis keturunan disusur-mundur sampai ke Raja Singaraja, Bali, dan dari pihak ayah disusur-mundur sampai ke Sultan Kediri, yang kelak berurusan dengan kerajaan besar Majapahit.
Sedangkan Soeharto hanya menyebut Desa Kemusuk, desa kecil di luar Kota Yogyakarta, dan pangkat bapaknya seorang "ulu-ulu, petugas desa pengatur air". Kedua, bukan saja keningratan akan tetapi adanya suatu suratan takdir bahwa Soekarno, bukan karena kemauannya atau keinginan pribadinya akan tetapi sejarah menetapkan demikian, akan dan bahkan harus memimpin Indonesia karena dari asal-muasal sebagai bagian dari the ruling class. Ketiga, meski dengan seluruh kesadaran tentang "silsilah" ke masa lalu dan suratan takdir ke masa depan tidak satu kata pun disebut Soekarno tentang harta, milik, atau kekayaan apa pun. Sebaliknya, Soeharto sudah dalam halaman-halaman pertama membicarakan harta-tanah sejengkal, tanah jabatan, pangkat bapaknya, yang dalam halaman-halaman susulannya berbicara lagi tentang kambing, baju dan lain-lain lagi-meski semuanya dihubungkan dengan "...banyak penderitaan yang mungkin tidak dialami oleh orang-orang lain".
Keempat, Soekarno bukan saja berbicara tentang keningratan, suratan takdir, kelas berkuasa dan memerintah akan tetapi tentang freedom of the people, suatu cita-cita abstrak-filosofis tinggi yang mencerminkan idealisme Soekarno-isch. Semuanya ini tentu saja berhubungan dengan kekuasaan, power, akan tetapi Soekarno tidak berbicara tentang kekuasaan dirinya. Dia berbicara tentang kelas berkuasa dan bukan tentang dirinya dan kekuasaan akan tetapi suratan takdir untuk memimpin.
Dalam hal Soeharto bisa dilihat sesuatu yang berbeda karena Soeharto berbicara tentang kekuasaan. Hal itu bisa diperiksa hanya dalam satu halaman sebelumnya ketika Soeharto kepada pewawancara untuk penulisan bukunya, dengan bangga dan sedikit sombong, mengenang saat ketika dia berdiri di depan forum dunia tahun 1985 di Food and Agriculture Organization, FAO, milik PBB, di Kota Roma:
Saudara bayangkan, seorang yang lebih dari enam puluh tahun ke belakang masih anak bermandi lumpur di tengah kehidupan petani di Desa Kemusuk saat itu naik mimbar dan bicara di depan sekian banyak ahli dan negarawan dunia, sebagai pemimpin rakyat yang baru berhasil memecahkan persoalan yang paling besar bagi lebih dari 160 juta mulut.
Suatu loncatan besar dari suatu desa kecil di Yogyakarta, ke Roma, kota metropolitan; dari seorang anak berlumur lumpur di Kemusuk yang langsung dihubungkan dengan mimbar yang harus dipahami dalam arti ex cathedra, dan berbicara, yang juga harus dipahami lebih dalam arti memberikan maklumat di depan para ahli dan negarawan dunia. Dia menyebut dirinya pemimpin rakyat sambil menjejerkan prestasinya-bukan dalam hubungan dengan freedom of the people akan tetapi dengan kemampuannya memecahkan soal paling besar; bukan soal abstrak-filosofis Soekarno-isch akan tetapi persoalan "lebih dari 160 juta mulut". Ketika dia menyebut rakyat maka dia reduksikan rakyat itu menjadi bukan orang akan tetapi mulut.
* Daniel Dhakidae Kepala Litbang Kompas
Selepas ini: Satu Abad Bersama Nusantara